Penulis: Furqon Bunyamin Husein | Editor in Chief Radar Indonesia News
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Dalam imajinasi modern, negara sering diposisikan sebagai pemegang otoritas tertinggi: pembuat hukum, pengatur pasar, dan penjaga keadilan sosial. Namun sejarah panjang peradaban justru menunjukkan gambaran yang lebih kompleks.
Fakta empiris mengungkap bahwa di balik simbol kedaulatan negara, sering kali terdapat kekuatan lain yang bekerja lebih senyap namun menentukan – para kapitalist baik dalam konteks nasional maupun global.
Fenomena ketika kekuatan ekonomi ini mampu melampaui bahkan menundukkan kekuasaan negara bukanlah gejala baru. Ia memiliki akar sejarah yang panjang, serta telah menjadi perhatian para sejarawan, filsuf, dan ilmuwan sosial dari masa ke masa.
Akar Historis: Dari Pedagang ke Penguasa Bayangan
Sejarawan ekonomi Fernand Braudel, tokoh mazhab Annales Prancis menegaskan bahwa kapitalisme tidak identik dengan pasar bebas. Dalam karya monumentalnya Civilization and Capitalism, Braudel menyebut kapitalisme justru berkembang di “lapisan atas” ekonomi, di mana segelintir elite menguasai jaringan perdagangan, perbankan, dan politik. Negara, menurut Braudel, sering kali bukan pengendali kapitalisme, melainkan sebagai mitra bahkan pelayannya.
Pandangan ini selaras dengan pengalaman Eropa abad pertengahan hingga awal modern. Negara-negara kota seperti Venesia, Genoa, dan Firenze memperlihatkan bagaimana para bankir dan saudagar mampu menentukan arah kebijakan politik, perang, hingga diplomasi.
Keluarga Medici, misalnya, bukan hanya aktor ekonomi, tetapi penentu politik dan bahkan urusan keagamaan di Vatikan.
Sejarawan Inggris, E. J. Hobsbawm, dalam The Age of Capital, menegaskan bahwa abad ke-19 adalah masa ketika negara bangsa tumbuh seiring dengan ekspansi kapitalisme industri. Namun pertumbuhan itu tidak netral.
Negara kerap menjadi alat untuk melindungi kepentingan modal—melalui kolonialisme, hukum kepemilikan, dan penaklukan pasar baru—atas nama kemajuan, ekonomi dan modernisasi.
Kritik Klasik: Negara sebagai Alat Kelas Berkuasa
Karl Marx adalah tokoh yang paling keras mengkritik relasi antara negara dan kapitalisme. Dalam The Communist Manifesto, Marx menyebut negara modern sebagai “komite eksekutif bagi kepentingan kelas borjuis.” Bagi Marx, hukum, kebijakan, dan institusi negara tidak berdiri di ruang hampa, melainkan lahir dari struktur ekonomi yang timpang.
Pandangan ini kemudian diperkaya oleh Antonio Gramsci. Ia tidak hanya melihat dominasi kapitalisme melalui kekuatan koersif negara, tetapi juga melalui hegemoni budaya. Menurut Gramsci, kapitalisme bertahan karena berhasil menjadikan kepentingannya seolah-olah sebagai kepentingan bersama. Negara, media, pendidikan, dan agama menjadi instrumen untuk menormalisasi ketimpangan.
Era Modern: Kapitalisme Global dan Negara yang Terbatas
Memasuki abad ke-20 dan ke-21, relasi ini semakin kompleks. Ilmuwan politik Susan Strange memperkenalkan istilah structural power, yakni kekuatan untuk menentukan aturan main global.
Dalam pandangannya, korporasi multinasional, lembaga keuangan internasional, dan pasar global sering kali memiliki daya tekan lebih besar dibanding negara, terutama negara berkembang.
Ekonom pemenang Nobel, Joseph Stiglitz, juga mengkritik bagaimana neoliberalisme membuat negara kehilangan kedaulatannya.
Dalam Globalization and Its Discontents, Stiglitz menunjukkan bagaimana kebijakan yang didikte lembaga keuangan global sering memaksa negara mengorbankan kepentingan rakyat demi stabilitas pasar dan kepercayaan investor.
Sementara itu, sejarawan kontemporer Quinn Slobodian menyoroti bagaimana arsitektur ekonomi global sengaja dirancang untuk “melindungi kapital dari demokrasi.” Negara tetap ada, tetapi ruang geraknya dibatasi agar tidak mengganggu kebebasan modal.
Negara di Persimpangan Jalan
Pertanyaan pentingnya bukan lagi apakah kapitalisme berada di atas negara, melainkan sejauh mana negara masih mampu merebut kembali mandatnya sebagai pelindung kepentingan publik.
Sejarah menunjukkan bahwa negara bisa menjadi alat emansipasi—melalui kebijakan kesejahteraan, regulasi ketat, dan keberpihakan sosial—tetapi juga bisa berubah menjadi perpanjangan tangan dari para pemodal alias kaum kapitalis.
Di tengah krisis ekologi, ketimpangan sosial, dan komersialisasi hampir seluruh aspek kehidupan, relasi negara dan kapitalisme kembali diuji. Apakah negara akan terus tunduk pada logika akumulasi, atau berani menata ulang arah pembangunan demi keadilan sosial dan keberlanjutan?
Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya ditentukan oleh elite politik dan ekonomi, tetapi juga oleh kesadaran publik. Sebab, sebagaimana diingatkan para sejarawan, kekuasaan modal tumbuh subur bukan hanya karena kekuatannya sendiri, tetapi juga karena minimnya perlawanan yang terorganisir.[]
Referensi:
1. Braudel, Fernand. Civilization and Capitalism, 15th–18th Century. University of California Press. 2. Hobsbawm, E. J. The Age of Capital: 1848–1875. Vintage Books. 3. Marx, Karl & Engels, Friedrich. The Communist Manifesto. 4. Gramsci, Antonio. Selections from the Prison Notebooks. 5. Strange, Susan. The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy. 6. Stiglitz, Joseph E. Globalization and Its Discontents. 7. Slobodian, Quinn. Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism.[]

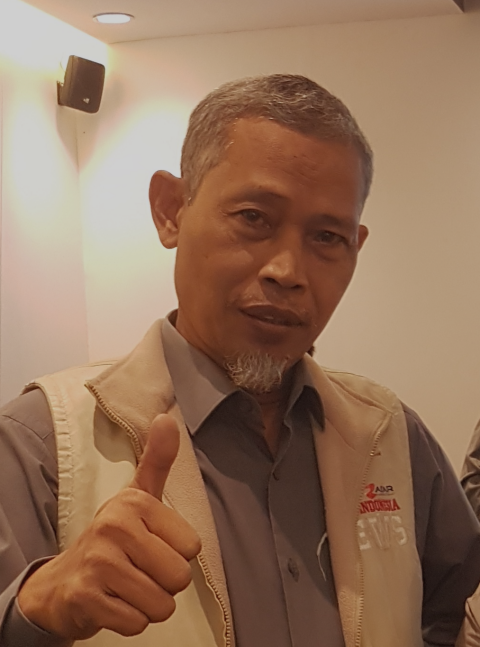













Comment