Penulis: Amir Kumadin | Alumni IAIN Walisongo Semarang, Direktur Penerbit Intuisi Press, Penulis Lebih dari 15 Judul Buku
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Membaca judul di atas barangkali membuat sebagian pembaca mengernyitkan dahi. Tidak berhenti di situ, judul ini bisa saja memantik rasa penasaran, bahkan menimbulkan rasa jengah. “Di zaman serba praktis seperti sekarang, masihkah kita diajak berbincang filsafat dan tasawuf yang rumit, berbelit, dan terasa jauh dari realitas?”
Namun justru di situlah letak ujiannya. Hidup ini memang tidak pernah steril dari masalah, tantangan, dan rintangan. Bahkan, hanya melalui kerumitan dan kesulitan itulah manusia ditempa untuk menjadi dirinya yang sejati. Tanpa ujian, tak akan ada pendewasaan. Tanpa pergulatan, tak akan lahir kebijaksanaan.
Untuk memahami judul dan gagasan utama tulisan ini, pembaca memang perlu diajak berfilsafat—dalam makna yang sebenar-benarnya. Sebab, banyak sabda Nabi Muhammad saw yang tidak hanya mengandung makna normatif, tetapi juga lapisan-lapisan makna filosofis dan spiritual yang dalam, bertingkat, dan tidak selalu terjangkau oleh logika verbal semata.
Meski demikian, tidak ada alasan untuk takut apalagi fobia terhadap filsafat. Filsafat sejati bukan untuk mempersulit persoalan, melainkan justru membantu manusia memahami hakikat persoalan secara lebih jernih. Secara etimologis, filsafat adalah cinta kepada kebijaksanaan.
Kebijaksanaan yang paling hakiki adalah cinta kepada Tuhan. Maka, cinta kepada Tuhan itulah filsafat yang paling murni. Sebaliknya, jika ada pemikiran yang justru mengaburkan makna, mempermainkan Tuhan, dan menjerumuskan akal, maka itu bukan filsafat, melainkan kekacauan nalar yang lahir dari kedangkalan berpikir.
Mari kita cerna yang tampak rumit itu agar menjadi serenyah mengunyah kacang atom.
Nabi Muhammad saw bersabda: “Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (Muttafaqun ‘Alaih).
Dalam proses mencintai orang lain, ego kerap menjadi penghalang utama. Ego berdiri di antara subjek yang mencintai dan objek yang dicintai. Karena itu, cinta sejati hanya mungkin hadir ketika ego tidak lagi menjadi penguasa.
Seseorang baru bisa disebut benar-benar mencintai apabila ia mendahulukan kepentingan, kehendak, dan kebutuhan yang dicintainya di atas kepentingan dirinya sendiri. Di situlah esensi cinta bekerja—tanpa syarat, tanpa pamrih, dan tanpa dominasi ego.
Pertanyaannya kemudian, apa yang dimaksud dengan “mencintai dirinya sendiri” dalam hadis tersebut? Jika pertanyaan ini belum terjawab, maka sejatinya manusia belum sampai pada tahap mencintai dirinya sendiri. Adapun yang dimaksud “mencintai dirinya sendiri” justru adalah “mencintai saudaranya”.
Kata saudara di sini bersifat universal- segala sesuatu yang berada di luar diri kita. Mengapa demikian? Karena jalan menuju cinta diri tidak pernah langsung, melainkan harus melalui cinta kepada yang lain.
Saat seseorang mencintai orang lain, hakikatnya ia sedang mencintai dirinya sendiri. Dengan kata lain, cinta diri hanya mungkin lahir melalui cinta kepada realitas di luar diri. Karena itu, mencintai saudara—dalam makna luas—adalah ekuivalen dengan mencintai diri sendiri.
Bahkan dalam aspek biologis dan personal sekalipun, cinta diri menuntut pengikisan ego. Ketika seseorang ingin sehat, ia harus disiplin menjaga pola makan, berolahraga, dan mengubah gaya hidup.
Ketika ingin sembuh, ia harus taat minum obat, berpikir positif, dan merawat tubuhnya. Semua itu menuntut pengorbanan kenyamanan ego.
Maka, mencintai apa pun—manusia lain, alam semesta, bahkan Allah dan Rasul-Nya—hanya mungkin terjadi jika seseorang bersedia menanggalkan egoisme dan tunduk sepenuhnya pada kehendak yang dicintainya. Tanpa itu, cinta hanya ilusi.
Mengikis ego adalah syarat mutlak dalam perjalanan cinta: cinta pada diri sendiri, cinta pada sesama, cinta pada alam, dan cinta pada Allah serta Rasul-Nya.
Hukum kehidupan menunjukkan satu hal pasti: apa yang Anda cintai, pada akhirnya akan kembali mencintai Anda. Itulah sunatullah yang bekerja tanpa kompromi. Cinta tidak pernah hilang; ia selalu kembali ke sumbernya.
Karena itu, tidak ada alasan untuk berhenti mencintai. Mencintai adalah investasi spiritual yang tidak pernah merugi. Ketika seseorang mencintai sesama dan seluruh ciptaan-Nya, pada saat yang sama ia sedang mencintai dirinya sendiri, sedang menaati perintah-Nya, dan sedang beribadah kepada-Nya.
Ketika Allah mencintai seorang hamba, itulah puncak cinta diri yang sesungguhnya. Sebaliknya, murka-Nya adalah tanda bahwa manusia sedang menyakiti dan membinasakan dirinya sendiri, baik di dunia maupun di akhirat.
Maka, sekali lagi: jalan untuk mencintai diri sendiri tidak pernah langsung. Satu-satunya jalan adalah mencintai orang lain, mencintai alam semesta, dan mencintai Allah serta Rasul-Nya terlebih dahulu. Tidak ada jalan lain menuju Roma.
Dalam selimut mendung dan rintik hujan gerimis, jari-jemari ini terus bergerak, seakan berbisik, izinkan aku menyingkap tabir-tabir sunatullah yang masih luput dari pandangan banyak manusia.[]

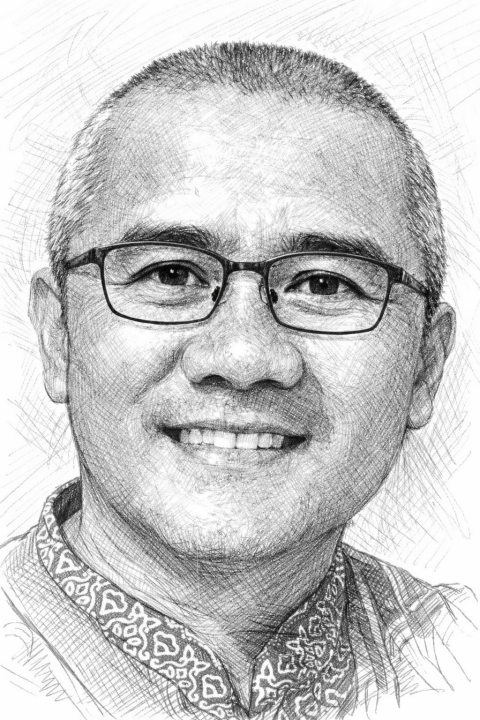











Comment